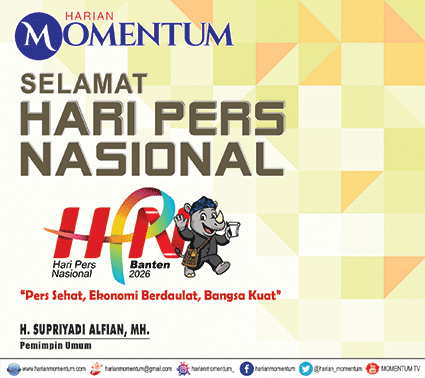MOMENTUM -- Artikel ini mengkritisi paradoks kedaulatan digital di Indonesia: di satu sisi pemerintah menyerukan kemandirian teknologi dan keamanan data, namun di sisi lain masih bergantung pada platform asing. Melalui pengalaman penulis sebagai pengembang aplikasi Recommedia, artikel ini menyoroti bias institusional terhadap merek luar negeri serta pentingnya kepercayaan terhadap inovasi lokal. Penulis juga menyinggung kasus CoreTax yang dikritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai simbol ketergantungan digital yang berisiko.
Kedaulatan digital telah menjadi mantra dalam berbagai forum kebijakan publik. Kita sering mendengar pejabat berbicara tentang pentingnya data nasional, server dalam negeri, dan transformasi digital yang mandiri. Namun di lapangan, semangat itu sering kandas pada praktik sederhana: lembaga pemerintah masih lebih percaya pada platform asing ketimbang karya anak bangsa.
Padahal, kedaulatan digital tidak dibangun oleh peraturan atau pidato, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari — termasuk ketika memilih aplikasi atau sistem untuk mengelola data publik.
Ketika Nama Besar Menutup Mata pada Karya Sendiri
Saya adalah pengembang Recommedia, sebuah platform analisis media digital buatan Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk membantu lembaga publik, BUMN, dan institusi pemerintah memantau percakapan daring, membaca opini publik, dan mengukur efektivitas komunikasi. Semuanya dibangun dan dikelola di dalam negeri: server, sistem, hingga analisis datanya. Tidak ada satu pun informasi yang keluar dari yurisdiksi Indonesia.
Namun saat menawarkan Recommedia ke salah satu lembaga pemerintah, saya dihadapkan pada pertanyaan yang akrab: “Brand24 hanya 999 dolar per bulan. Mengapa Recommedia bisa lebih mahal?”
Pertanyaan itu terdengar logis, tetapi mencerminkan persoalan mendasar: kita masih menilai teknologi dari label dan harga, bukan dari nilai strategisnya. Recommedia memang lebih mahal, tetapi karena menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dari luar — kendali penuh atas data, kemampuan kustomisasi, server di dalam negeri, dan analisis manusia yang memahami konteks sosial Indonesia.
Saya memahami alasan orang memilih platform asing: tampilannya mapan, fiturnya lengkap, dan reputasinya global. Tapi setelah mencoba Brand24 sendiri, saya yakin Recommedia tidak kalah. Bahkan dalam beberapa hal, lebih unggul dan lebih relevan untuk kebutuhan negeri ini.
Recommedia karena menjadi bagian dari SMSI, asosiasi para produsen berita online seluruh indonesia, terhubung dengan lebih dari 3.000 media lokal di seluruh Indonesia. Ini penting bagi lembaga publik yang kerap menyalurkan rilis berita atau membeli placement di media daerah, tetapi tidak memiliki alat ukur untuk memantau hasilnya. Dengan Recommedia, semua itu bisa dipantau secara real-time — media mana yang menayangkan, di daerah mana, dan seberapa besar eksposurnya.
Alih-alih berhenti pada deretan angka dan grafik, Recommedia berupaya menghadirkan pemahaman. Setiap tren dan pola yang muncul tidak dibiarkan bicara sendiri, tetapi dibaca dan ditafsirkan oleh tim analis komunikasi yang memahami konteks sosial masyarakat Indonesia. Kami percaya bahwa data tanpa makna hanyalah deretan angka dingin; yang memberi nyawa adalah interpretasi—terutama di negeri yang wacananya sering disampaikan dengan lapisan humor, sindiran, bahkan sarkasme halus yang kerap luput dari algoritma asing.
Masalahnya Bukan Teknologinya, Tapi Cara Pandangnya
Masalah sebenarnya bukan pada kemampuan teknologi kita, melainkan pada cara pandang terhadap karya bangsa sendiri. Ada semacam inferiority complex yang membuat lembaga publik lebih percaya pada merek global, seolah-olah yang buatan luar pasti lebih hebat.
Fenomena ini tampak jelas dalam kasus CoreTax System, sistem perpajakan terpadu milik Direktorat Jenderal Pajak. Proyek bernilai besar itu digarap oleh perusahaan luar negeri asal Korea Selatan, LG CNS, dan sempat menghadapi berbagai kendala di tahap implementasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian mengkritik pendekatan yang terlalu bergantung pada pihak asing, mengingatkan bahwa Indonesia punya banyak talenta digital mumpuni yang sering diabaikan.
Pernyataan Purbaya menyentuh akar persoalan: kita terlalu sering terpesona pada merek dan tenaga luar, padahal kemampuan dalam negeri tak kalah—bahkan lebih paham konteks lokal. CoreTax seharusnya menjadi pelajaran bahwa kedaulatan digital tak akan tercapai bila sistem vital bangsa terus diserahkan ke tangan asing.
Kedaulatan Digital Bukan Sekadar Lokasi Server
Selama ini, wacana kedaulatan digital sering disederhanakan menjadi soal lokasi server. Seolah-olah jika data disimpan di dalam negeri, maka kita sudah berdaulat. Padahal, kedaulatan digital sejati jauh lebih kompleks.
Ia mencakup penguasaan infrastruktur, algoritma, dan kompetensi sumber daya manusia. Negara tidak akan benar-benar berdaulat jika hanya menyimpan datanya di sini, tetapi membiarkan proses analisis dan kecerdasan buatan dikendalikan pihak luar.
Aspek ekonominya pun besar. Setiap lembaga publik yang berlangganan platform asing sebenarnya mengalirkan uang ke luar negeri — dan setiap rupiah itu tidak akan kembali. Sebaliknya, ketika pemerintah menggunakan solusi lokal, dana itu berputar di dalam negeri: menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekosistem riset, dan menumbuhkan kapasitas teknologi nasional.
Selain infrastruktur dan ekonomi, ada dimensi kultural yang sering terabaikan. Teknologi asing membawa nilai dan cara pandang sendiri. Jika seluruh sistem digital kita didesain oleh pihak luar, lama-kelamaan kita akan melihat diri sendiri melalui algoritma mereka. Kita akan membaca opini publik, perilaku masyarakat, bahkan reputasi lembaga negara dari cara pandang yang bukan milik kita.
Kepercayaan Adalah Infrastruktur yang Sebenarnya
Kedaulatan digital sejatinya adalah soal kepercayaan. Pemerintah perlu percaya bahwa anak bangsa mampu membangun sistem yang handal. Masyarakat perlu percaya bahwa produk lokal bukan sekadar alternatif, tetapi pilihan strategis. Dan pengembang lokal perlu percaya bahwa kerja keras mereka akan dihargai, bukan dipinggirkan.
Kepercayaan adalah infrastruktur tak kasat mata yang menopang semua sistem digital. Tanpanya, semua teknologi secanggih apa pun hanya akan menjadi menara pasir. Kita bisa punya ribuan server di tanah air, tapi jika pengambil kebijakan masih lebih percaya pada platform asing, maka kedaulatan digital hanya akan jadi jargon kosong.
Ketika sebuah lembaga publik memilih menggunakan produk lokal, mereka sesungguhnya sedang membangun lapisan pertama dari kedaulatan digital bangsa. Mereka sedang mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya pasar pengguna, tetapi juga produsen pengetahuan dan teknologi.
Dari Keputusan Kecil, Lahir Kedaulatan Besar
Pengalaman saya dengan Recommedia dan Brand24 mungkin tampak sederhana, tapi sesungguhnya mencerminkan persoalan besar: bagaimana kita memandang diri sendiri. Kita sering berbicara lantang tentang kemandirian digital, tapi dalam praktiknya masih menggantungkan sistem vital bangsa pada pihak luar. Kita sering mengagumi kemampuan bangsa lain, tapi lupa bahwa di sekitar kita ada banyak talenta yang sama hebatnya.
Kasus CoreTax, pengalaman Recommedia, hingga banyak contoh lain menunjukkan satu hal: kita tidak kekurangan kemampuan—yang kurang hanyalah kepercayaan.
Kedaulatan digital bukan sekadar soal di mana data disimpan, tetapi siapa yang mengendalikannya. Dan mungkin, langkah pertama menuju kedaulatan itu tidak dimulai dari proyek miliaran, melainkan dari keputusan sederhana di ruang rapat kecil:
“Mari kita percayakan pada karya anak bangsa—karena mereka mampu, dan karena kedaulatan tidak bisa disubkontrakkan.” (**)
Oleh Yoga Rifai Hamzah - Pendiri dan pengembang Recommedia, platform analisis media digital buatan Indonesia, Pegiat Literasi, Tinggal di Pekalongan.
Editor: Muhammad Furqon