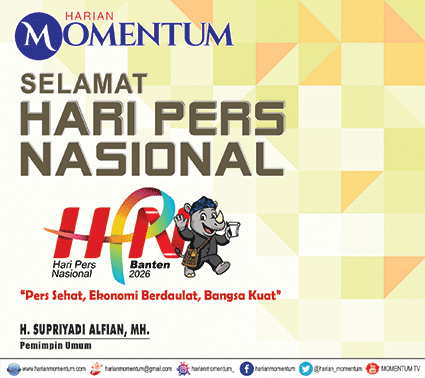MOMENTUM -- Di tengah hiruk pikuk politik negeri ini, mundurnya Rahayu Saraswati alias Saras dari kursi empuk DPR RI terasa seperti kisah fiksi. Anak muda, perempuan pula, justru memilih menanggalkan jabatan yang bagi banyak orang dianggap sebagai “puncak pencapaian.”
Sebuah tindakan langka. Bahkan nyaris absurd, jika dibandingkan dengan perilaku mayoritas politisi kita yang seolah rela mati-matian demi kekuasaan. Mulai dari menyulap suap menjadi “bantuan sosial,” merombak aturan dengan dalih “reformasi hukum,” hingga tak segan melanggar norma moral paling dasar.
Lihatlah sekitar. Jabatan bukan lagi amanah, melainkan ATM berjalan. Ia dipakai untuk menindas, mengintimidasi, bahkan memeras siapa saja demi menambah pundi-pundi kekayaan. Keserakahan dan ketamakan dipertontonkan tanpa rasa malu.
Budaya malu? Sudah lama wafat, dimakamkan tanpa doa. Mereka yang ketahuan menyeleweng masih bisa tersenyum di televisi, mengelak dengan gaya santai, bahkan merasa bangga dengan hasil rampasan. Korupsi, nepotisme, hingga jual-beli pengaruh—semua jadi tontonan harian.
Maka, ketika Saras pamit dari DPR dengan alasan etika, publik terhenyak. Bagaimana mungkin ada politisi rela mundur, sementara di luar sana banyak yang sudah terbukti bermasalah hanya sekadar “nonaktif,” lalu berharap publik cepat lupa? Sebut saja kasus Eko atau selebritas politik seperti Uya Uya yang masih nyaman dengan status abu-abu.
Ironisnya, di negeri ini, mundur karena kesalahan dianggap kelemahan. Padahal sejatinya, itu justru tanda integritas. Yang populer justru seni bertahan, meski aib terbongkar. Lebih hina lagi, ada yang malah bangga memamerkan hasil korupsi, seolah pahlawan bagi keluarga besar.
Langkah Saraswati memang tak serta-merta mengubah wajah politik yang bopeng. Namun setidaknya, ia berhasil menampar kesadaran kita: bahwa masih ada orang yang tahu malu, di tengah budaya malu yang sudah lama dikubur.
Di negeri yang menjadikan jabatan sebagai tambang emas, keberanian untuk mundur adalah revolusi kecil—meski hanya dilakukan seorang diri.
Terima kasih, Saras, telah memberi teladan sederhana, bahwa jabatan dan kekayaan bukan “tuhan” yang harus dibela mati-matian.
Setetes air memang tak mampu menyuburkan tanah yang tandus. Namun setetes demi setetes bisa menjadi aliran, lalu sungai, yang suatu hari—siapa tahu—akan membersihkan lumpur busuk yang menutupi negeri ini.
Tabik...!
Oleh Muhammad Furqon - Dewan Redaksi Harian Momentum
Editor: Muhammad Furqon